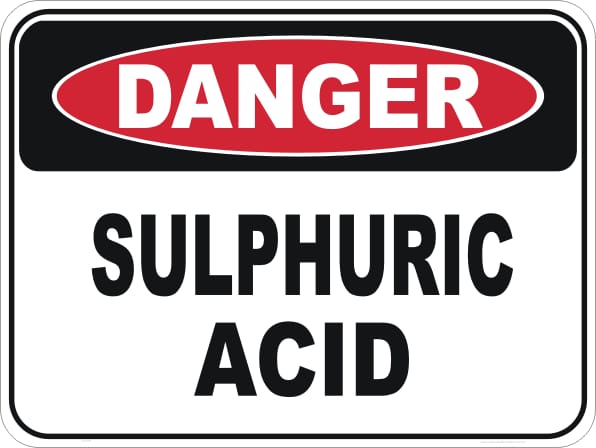
Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia
Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia
Gibran Rakabuming Raka telah ditetapkan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia secara sah dan konstitusional. Proses pemilihan telah selesai, keputusan hukum telah dibuat, dan negara bergerak maju. Dalam kerangka demokrasi prosedural, tidak ada yang bisa diperdebatkan lagi mengenai legalitas jabatannya. Konstitusi telah bekerja.
Namun demokrasi yang dewasa tidak berhenti pada legalitas. Demokrasi yang sehat justru hidup dari pertanyaan-pertanyaan lanjutan: tentang makna, kualitas, dan arah representasi kepemimpinan nasional yang dihasilkan.
Di titik inilah kegelisahan publik muncul.
Pertanyaan yang mengemuka sebenarnya sangat sederhana, tetapi dampaknya sangat dalam:
apakah Gibran benar-benar merepresentasikan anak muda Indonesia dari seluruh entitas kader bangsa?
Indonesia bukan negara yang miskin sumber daya manusia. Sejak lama, republik ini membangun ekosistem kaderisasi melalui banyak jalur. Partai politik mencetak kader melalui struktur dan ideologi. Pemerintah daerah melahirkan pemimpin yang teruji oleh kompleksitas birokrasi dan dinamika rakyat. Militer menyiapkan kader dengan disiplin, kepemimpinan strategis, dan manajemen krisis. Muhammadiyah dan NU membesarkan kader melalui pengabdian sosial, pendidikan, dan kerja-kerja keumatan. Pesantren membentuk pemimpin dengan basis moral dan spiritual. Perguruan tinggi melahirkan intelektual, teknokrat, dan pemikir kebijakan.
Semua jalur ini panjang, melelahkan, dan penuh seleksi. Tidak instan. Tidak mudah. Dan tidak semua orang mampu bertahan di dalamnya.
Di tengah realitas itu, pertanyaan publik menjadi sah untuk diajukan:
Gibran lahir dari jalur kaderisasi yang mana?
Apakah ia representasi kader partai yang tumbuh dari bawah dan diuji oleh konflik internal organisasi?
Apakah ia representasi kader pemerintah daerah yang melalui proses panjang birokrasi publik lintas level?
Apakah ia representasi kader militer dengan pengalaman komando dan pengabdian negara?
Apakah ia lahir dari rahim organisasi masyarakat besar seperti Muhammadiyah atau NU?
Apakah ia produk pesantren atau dunia akademik yang panjang proses intelektualnya?
Atau, secara jujur harus diakui, ia lahir dari jalur kekuasaan yang tidak tersedia bagi sebagian besar anak muda Indonesia?
Inilah inti persoalan representasi.
Menjadi pemimpin muda bukan sekadar soal usia biologis. Usia muda tidak otomatis menjadikan seseorang representasi generasi muda. Representasi menuntut kesamaan pengalaman struktural—mengalami keterbatasan yang sama, menghadapi sistem yang sama, dan melewati rintangan yang sama dengan mayoritas anak muda lain.
Jutaan anak muda Indonesia meniti hidup dari bawah. Mereka berjuang di organisasi, di kampus, di pesantren, di birokrasi daerah, di dunia profesional, bahkan di sektor informal. Mereka menunggu giliran, berkompetisi secara merit, gagal berkali-kali, lalu bangkit kembali. Sebagian besar dari mereka tahu bahwa jalan menuju kepemimpinan nasional adalah jalan panjang, berliku, dan sering kali tidak adil.
Ketika seorang anak muda berada di puncak kekuasaan tanpa melalui jalur umum tersebut, maka wajar jika muncul jarak psikologis. Bukan karena iri, bukan karena kebencian, melainkan karena rasa tidak terwakili. Bagi banyak anak muda, kisah Gibran bukan cermin harapan, melainkan anomali yang sulit ditiru.
Di sinilah demokrasi menghadapi ujian moralnya.
Demokrasi seharusnya mengirim pesan bahwa kepemimpinan adalah hasil dari kapasitas, pengalaman, dan integritas. Ketika yang terbaca justru akselerasi kekuasaan melalui kedekatan struktural, maka pesan meritokrasi menjadi kabur. Bukan hanya bagi generasi muda, tetapi bagi seluruh bangsa.
Lebih jauh lagi, jabatan wakil presiden bukan posisi simbolik belaka. Ia adalah bagian dari pusat pengambilan keputusan nasional. Ia mewakili wajah masa depan republik. Karena itu, publik berhak bertanya: nilai siapa yang akan ia perjuangkan? Kepentingan siapa yang akan ia dengarkan? Dan keberpihakan apa yang akan ia ambil ketika berhadapan dengan konflik kepentingan elite dan rakyat?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan status konstitusional semata. Jawabannya hanya bisa dibuktikan melalui kerja nyata, sikap politik, keberanian moral, dan konsistensi keberpihakan.
Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa banyak pemimpin sah secara hukum, tetapi gagal secara representasi. Sebaliknya, ada pula pemimpin yang lahir dari keraguan publik, tetapi mampu menebusnya dengan kerja dan keberanian. Gibran kini berada di persimpangan sejarah itu.
Ia telah memperoleh jabatan. Namun legitimasi sosiologis dan moral masih harus diperjuangkan.
Apabila Gibran ingin benar-benar menjadi wakil generasi muda Indonesia—dari partai, daerah, militer, ormas, pesantren, hingga kampus—maka ia harus melampaui label simbolik. Ia harus membuka ruang partisipasi yang nyata, mendengar suara yang selama ini terpinggirkan, dan membuktikan bahwa kekuasaan tidak selalu identik dengan privilese.
Karena pada akhirnya, demokrasi bukan hanya tentang siapa yang terpilih, tetapi tentang siapa yang benar-benar diwakili. Jabatan bisa diwariskan oleh sistem, tetapi kepercayaan publik hanya bisa diraih melalui keberanian berpihak pada kepentingan bangsa secara utuh.
Dan sejarah, seperti biasa, tidak pernah menilai dari awal cerita—melainkan dari akhir perjuangan.
SiS,Antarkita



