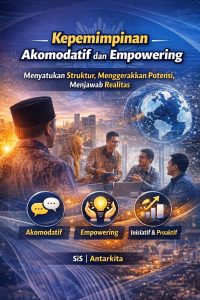Sihir Demokrasi
Sihir Demokrasi
Gibran terpilih secara konstitusional. Prosesnya sah, legal, dan tidak melanggar prosedur hukum negara. Dalam demokrasi elektoral, fakta itu sering dianggap sebagai penutup semua perdebatan. Namun demokrasi sejati tidak berhenti pada legalitas. Ia justru dimulai dari pertanyaan lanjutan yang lebih mendasar: apakah seseorang yang terpilih benar-benar mewakili realitas sosial yang diklaimnya wakili?
Pertanyaan itu mengemuka ketika Gibran ditempatkan sebagai simbol representasi anak muda Indonesia. Pertanyaan sederhana, bahkan terdengar wajar: apakah Gibran mewakili anak muda Indonesia dari seluruh entitas sosial yang ada—dari kampus, pesantren, organisasi kepemudaan, buruh muda, petani muda, pemuda daerah, hingga komunitas adat dan kelompok marginal? Anehnya, pertanyaan yang mudah diajukan ini justru sulit dijawab secara jujur dan cepat. Di sinilah bekerja apa yang bisa disebut sebagai sihir demokrasi.
Sihir demokrasi bukanlah kecurangan teknis, melainkan ilusi kolektif. Ia membuat kita percaya bahwa prosedur yang sah otomatis berarti representasi yang utuh. Demokrasi direduksi menjadi hitung-hitungan suara, sementara makna keterwakilan dikesampingkan. Ketika seseorang menang secara konstitusional, seolah semua pertanyaan tentang kualitas, kapasitas, dan konteks sosial menjadi tidak relevan.
Dua periode pemerintahan Jokowi telah berakhir secara administratif. Namun polemik yang menyertainya belum pernah benar-benar selesai. Jokowi hari ini masih menerima gaji pensiunan dan fasilitas negara, tetapi bersamaan dengan itu, kontroversi tetap mengiringi warisan kekuasaannya. Mulai dari kebijakan ekonomi-politik, relasi dengan oligarki, hingga isu ijazah yang terus dipertanyakan dan tak kunjung tuntas. Semua itu menunjukkan bahwa legitimasi elektoral tidak otomatis menutup ruang kritik.
Jokowi memenangkan dua kali pemilu secara sah. Namun pertanyaan yang jarang diajukan secara serius adalah: apakah kemenangan tersebut mencerminkan kualitas kepemimpinan terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia? Atau sekadar hasil dari momentum politik, kekuatan jaringan, dan pengelolaan persepsi publik?
Padahal Indonesia tidak pernah kekurangan kader. Bangsa ini melahirkan pemimpin dari berbagai jalur: kader partai politik yang matang secara ideologis, perwira militer dengan pengalaman strategis, kepala daerah dengan rekam jejak birokrasi, aktivis organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah dan NU, akademisi dari perguruan tinggi, ulama pesantren, hingga teknokrat dan profesional yang teruji di bidangnya. Semua entitas ini adalah sumber kepemimpinan yang sah dan berakar.
Lalu pertanyaan yang seharusnya wajar muncul: apakah Jokowi merupakan representasi dari keseluruhan spektrum kader tersebut? Jika jawabannya tidak mutlak, mengapa seolah-olah tidak ada pilihan lain?
Belum selesai polemik Jokowi, muncullah Gibran sebagai figur baru dalam panggung kekuasaan nasional. Sekali lagi, legitimasi konstitusional menjadi tameng utama. Namun pertanyaan representasi kembali mencuat. Apakah Gibran mewakili generasi muda Indonesia dalam seluruh keragamannya? Ataukah ia hanya mewakili sebagian kecil realitas sosial yang kemudian digeneralisasi secara politis?
Ironisnya, ketika pertanyaan “kalau bukan Gibran, lalu siapa?” diajukan, publik mendadak terdiam. Tidak ada jawaban cepat. Seolah bangsa ini kehabisan stok kepemimpinan muda. Padahal, dari seluruh entitas yang disebutkan, Indonesia telah melahirkan begitu banyak kader muda unggul—yang tumbuh melalui proses panjang, meritokrasi yang objektif, dan pengabdian nyata di akar rumput.
Mengapa jawaban itu tidak segera muncul? Bukan karena tidak ada, melainkan karena imajinasi politik kita telah dibatasi. Sihir demokrasi bekerja dengan cara yang halus: ia tidak melarang alternatif, tetapi membuat alternatif tampak mustahil. Ia menanamkan keyakinan bahwa hanya figur tertentu yang “layak”, sementara yang lain dianggap tidak relevan, tidak populer, atau tidak mungkin menang.
Akibatnya, demokrasi berubah menjadi ritual. Pemilu digelar, suara dihitung, pemenang diumumkan, lalu diskusi berhenti. Kita lupa bahwa demokrasi sejatinya adalah proses pendidikan politik, bukan sekadar mekanisme seleksi kekuasaan. Ketika masyarakat tidak lagi berani membayangkan pemimpin di luar nama-nama yang disodorkan sistem, maka demokrasi telah kehilangan daya pembebasnya.
Sihir demokrasi tidak menghancurkan demokrasi secara frontal. Ia justru melanggengkannya dalam bentuk yang dangkal. Demokrasi tetap berjalan, tetapi tanpa kedalaman. Legalitas tetap ada, tetapi tanpa refleksi. Pilihan tetap tersedia, tetapi imajinasi dikunci.
Dan selama bangsa ini terus terdiam ketika ditanya “kalau bukan dia, lalu siapa?”, selama itu pula kita akan terus berputar dalam lingkaran kekuasaan yang sempit—sementara kader-kader terbaik bangsa tetap berada di pinggir, menunggu demokrasi benar-benar dibebaskan dari sihirnya sendiri.
SiS
Antarkita