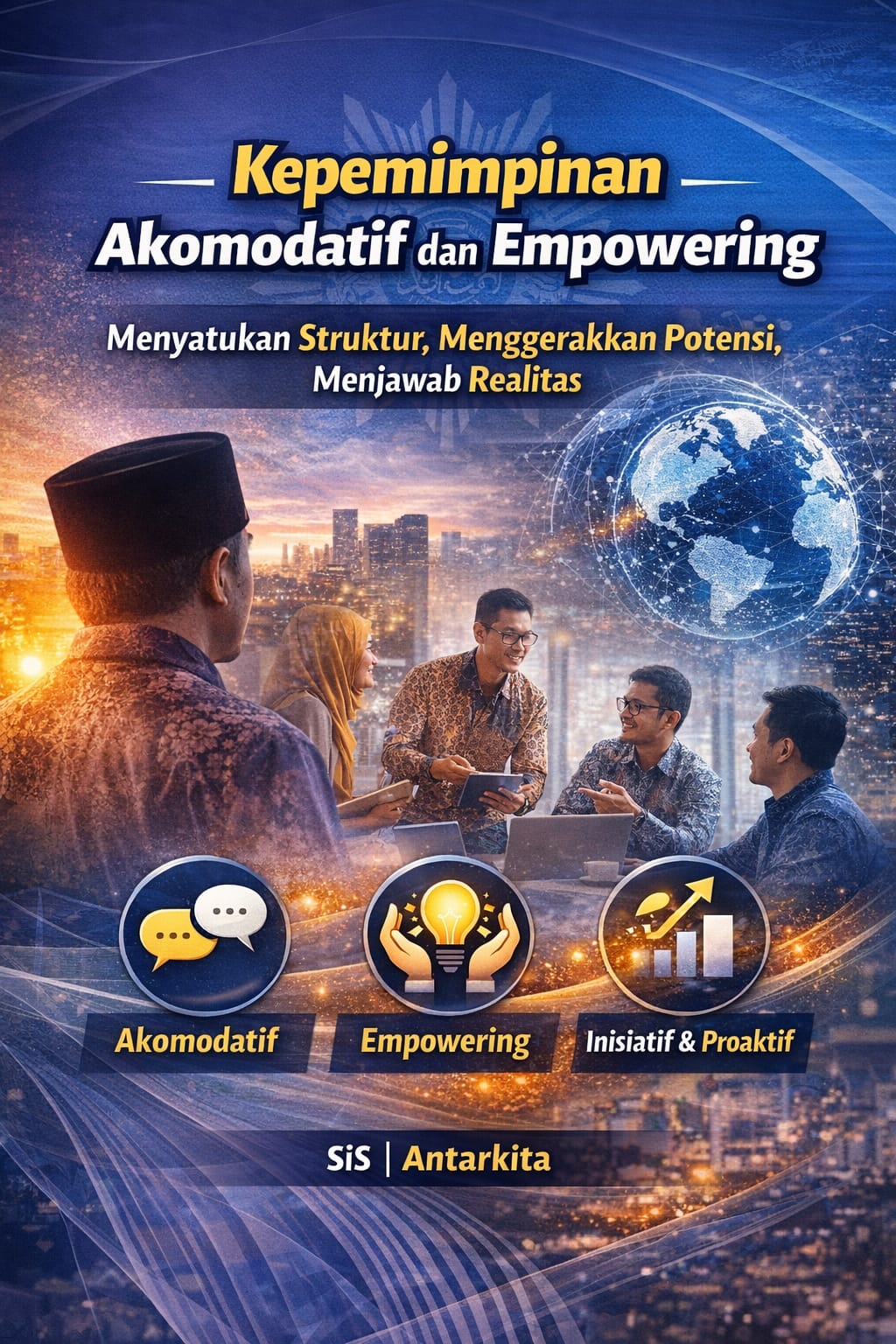
Kepemimpinan Akomodatif dan Empowering: Menyatukan Struktur, Menggerakkan Potensi, Menjawab Realitas
Kepemimpinan Akomodatif dan Empowering: Menyatukan Struktur, Menggerakkan Potensi, Menjawab Realitas
Oleh SiS, antarkita
Percepatan perubahan dunia hari ini berlangsung dalam ritme yang melampaui kebiasaan lama kita. Disrupsi teknologi digital, perubahan pola komunikasi, dinamika politik global, krisis lingkungan, pergeseran ekonomi, hingga perubahan gaya hidup generasi muda terjadi hampir serentak. Setiap persoalan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dan saling mempengaruhi. Dunia bergerak cepat—dan sering kali tidak memberi waktu panjang untuk sekadar berdiskusi tanpa keputusan.
Dalam konteks ini, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan menghadapi tantangan besar di abad keduanya. Tantangan itu bukan hanya soal mempertahankan eksistensi, tetapi memastikan relevansi. Relevansi terhadap problem umat, relevansi terhadap kebutuhan masyarakat, dan relevansi terhadap perubahan zaman yang sangat dinamis.
Namun di tengah kompleksitas persoalan kehidupan sehari-hari, muncul satu kenyataan yang perlu direnungkan secara jujur: adanya kesenjangan antara struktur organisasi dan realitas yang dihadapi masyarakat. Struktur memiliki logika tata kelola, mekanisme, hirarki, dan prosedur. Semua itu penting untuk menjaga ketertiban dan kesinambungan organisasi. Tetapi kehidupan nyata sering kali tidak berjalan sesuai alur administratif. Ia mendesak, spontan, dan membutuhkan respon segera.
Ketika masyarakat menghadapi persoalan ekonomi keluarga, krisis moral generasi muda, dampak teknologi terhadap nilai-nilai sosial, atau persoalan kebijakan publik yang merugikan, respon yang lambat akan terasa sebagai ketidakhadiran. Di sinilah jarak itu terasa: antara “istana struktur organisasi” dan denyut kehidupan sehari-hari.
Padahal, jika ditelisik lebih dalam, Muhammadiyah tidak kekurangan sumber daya manusia. Di berbagai daerah dan sektor, terdapat banyak kader yang memiliki kapasitas intelektual, pengalaman profesional, jejaring luas, dan kepekaan sosial yang tinggi. Mereka hadir sebagai akademisi, dokter, pengusaha, aktivis sosial, teknokrat, pemikir muda, dan profesional di berbagai bidang strategis.
Sayangnya, tidak semua potensi tersebut terakomodasi secara optimal oleh struktur yang ada. Sebagian kader belum menemukan ruang aktualisasi yang sesuai dengan kapasitasnya. Sebagian gagasan berhenti pada wacana karena tidak menemukan kanal struktural yang lentur. Sebagian energi bahkan memilih bergerak sendiri di luar koordinasi, karena merasa struktur terlalu lambat merespon.
Di sisi lain, harus diakui pula bahwa keberanian untuk mengambil inisiatif gagasan masih relatif rendah. Budaya menunggu instruksi, kekhawatiran dianggap melangkahi kewenangan, atau rasa sungkan terhadap senioritas sering membuat kader memilih aman dalam posisi pasif. Akibatnya, ruang-ruang kosong tidak segera terisi, dan peluang perubahan terlewatkan.
Kondisi inilah yang perlahan membentuk jurang pemisah antara kehidupan nyata dan struktur organisasi. Struktur menjadi simbol formalitas, sementara kehidupan berjalan dengan logikanya sendiri. Jika jurang ini dibiarkan, maka akan tumbuh apatisme. Kader merasa jauh dari pengambilan keputusan, dan masyarakat merasa jauh dari kehadiran organisasi.
Di sinilah kebutuhan mendesak akan kepemimpinan yang akomodatif dan empowering.
Kepemimpinan akomodatif adalah kepemimpinan yang bersedia membuka pintu dialog selebar-lebarnya. Ia tidak alergi terhadap kritik, tidak defensif terhadap gagasan baru, dan tidak merasa terancam oleh kader-kader potensial. Ia mampu melihat perbedaan sebagai kekayaan, bukan ancaman. Sikap akomodatif menciptakan atmosfer organisasi yang inklusif—di mana setiap kader merasa dihargai, didengar, dan diberi ruang.
Namun akomodatif saja belum cukup. Kepemimpinan harus sekaligus empowering—memberdayakan. Artinya, pemimpin tidak hanya menampung aspirasi, tetapi juga memberikan kepercayaan dan otoritas yang proporsional. Memberi mandat, mendorong eksperimen, dan memberi dukungan moral maupun struktural agar gagasan dapat diimplementasikan.
Kepemimpinan empowering menggeser paradigma dari “semua harus melalui saya” menjadi “bagaimana saya memampukan orang lain bergerak.” Ia membangun sistem yang memungkinkan kader bertumbuh, bukan sistem yang membuat kader bergantung. Ia melahirkan banyak pusat inisiatif, bukan satu pusat kendali yang terlalu sentralistik.
Namun perubahan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan. Kesadaran inisiatif dan sikap proaktif dari kader juga menjadi kunci. Setiap kader perlu menyadari bahwa gerakan ini bukan milik struktur semata, tetapi milik bersama. Tidak semua gagasan harus menunggu undangan. Tidak semua langkah harus diawali oleh instruksi formal. Dalam koridor nilai dan manhaj gerakan, inisiatif adalah bentuk tanggung jawab, bukan pelanggaran.
Ketika kepemimpinan bersikap akomodatif dan empowering, dan kader berani mengambil inisiatif secara proaktif, maka jurang antara struktur dan realitas akan menyempit. Struktur tidak lagi terasa sebagai menara gading, melainkan sebagai pusat koordinasi gerakan yang hidup. Kehidupan nyata tidak lagi terasa jauh, karena respon hadir secara cepat, relevan, dan kontekstual.
Percepatan perubahan dunia tidak bisa dihentikan. Yang bisa dilakukan adalah mempercepat kapasitas respon kita. Bukan dengan mengabaikan struktur, tetapi dengan membuat struktur lebih lentur, lebih terbuka, dan lebih memberdayakan.
Pada akhirnya, kepemimpinan yang akomodatif dan empowering bukan sekadar gaya manajerial, melainkan kebutuhan strategis. Ia adalah jembatan antara visi besar organisasi dan realitas konkret kehidupan. Ia adalah cara untuk memastikan bahwa potensi besar kader tidak terpendam, dan harapan besar umat tidak berujung pada kekecewaan.
Jika keberanian untuk berinisiatif tumbuh, jika ruang partisipasi dibuka, dan jika kepercayaan diperluas, maka Muhammadiyah akan tetap menjadi gerakan yang hidup—bukan hanya kokoh dalam struktur, tetapi kuat dalam aksi dan nyata dalam solusi.
Karena di tengah dunia yang bergerak cepat, yang dibutuhkan bukan hanya organisasi yang tertib, tetapi organisasi yang tanggap, adaptif, dan memberdayakan.



